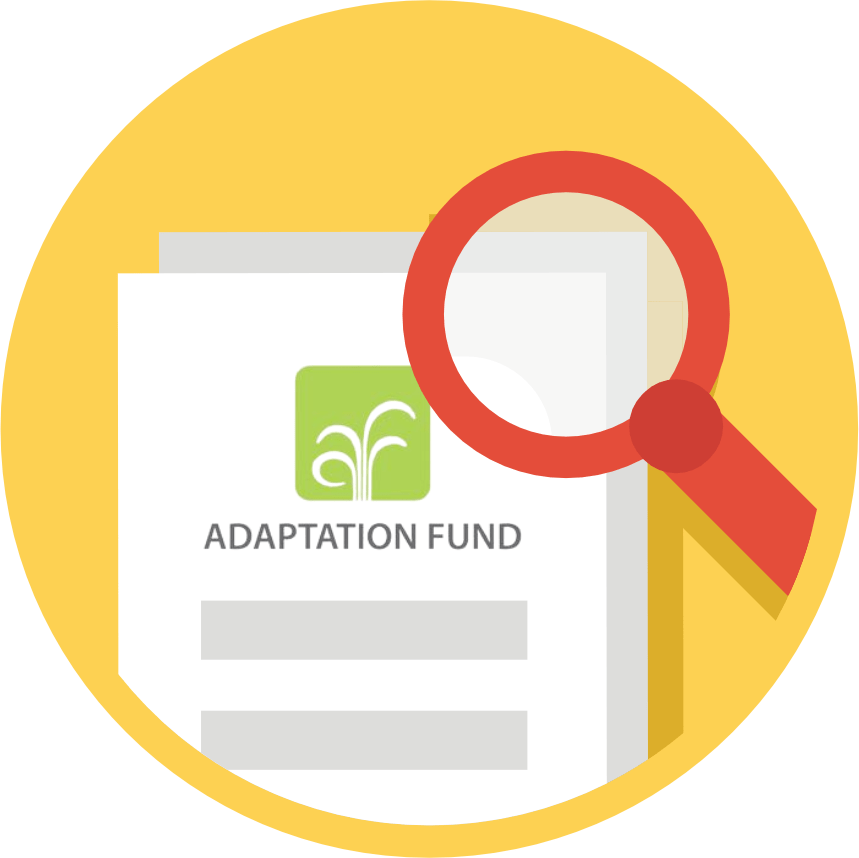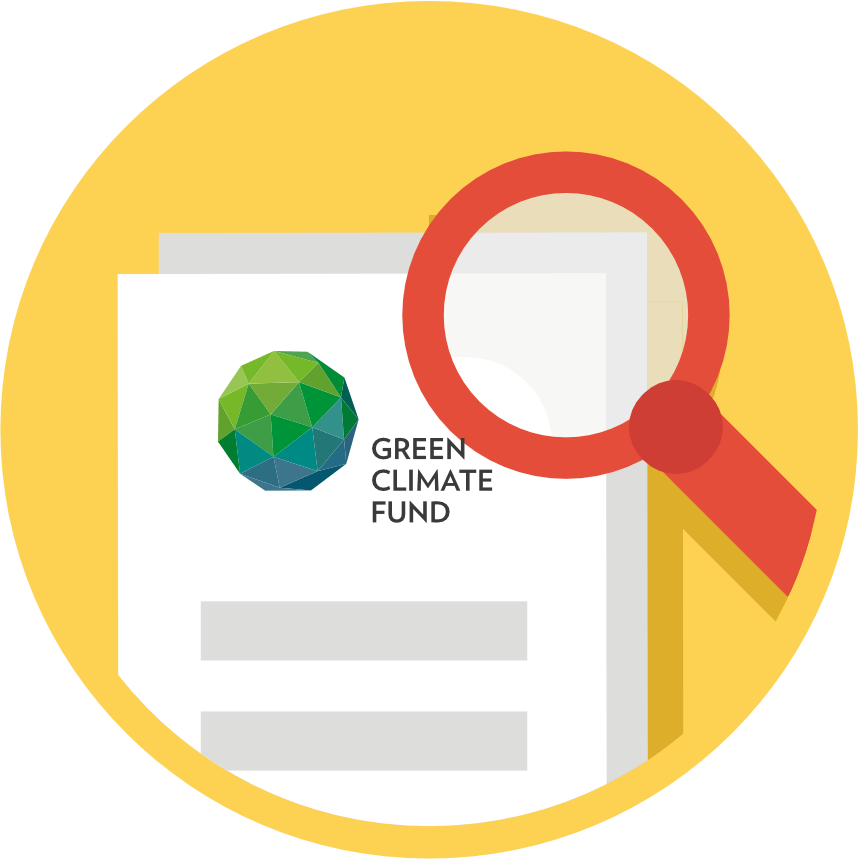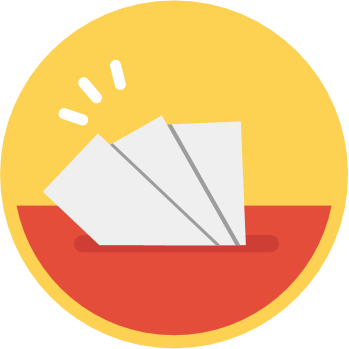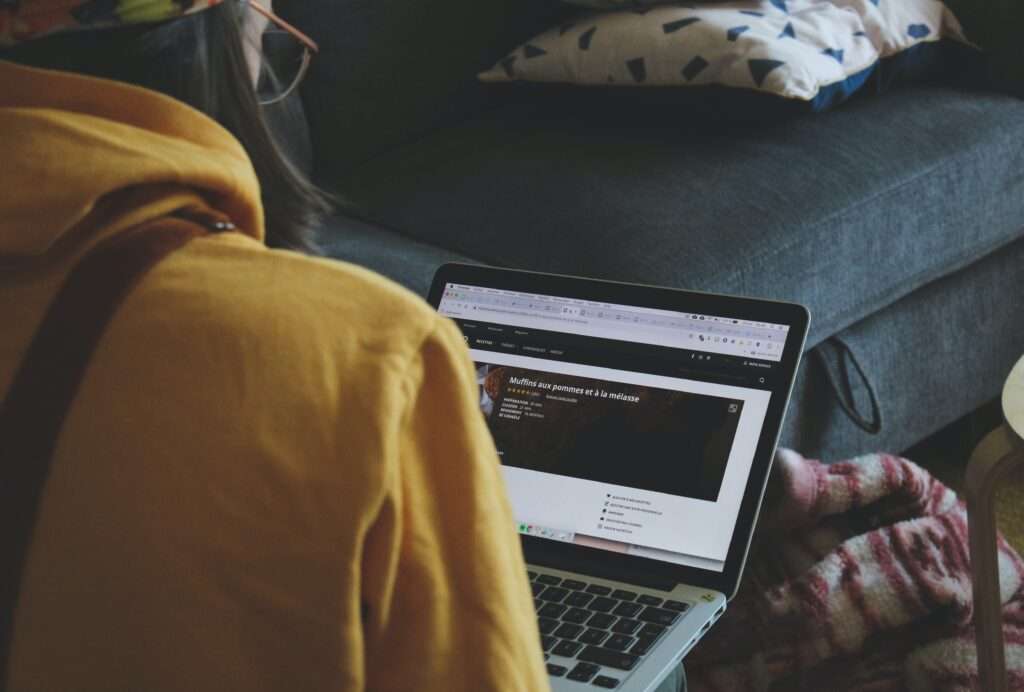
Pandemi global COVID-19 telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan rakyatnya. Internet dan teknologi telah digunakan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melacak, memasarkan, dan menginformasikan kebijakan. Namun, di balik peningkatan penggunaan teknologi ini terdapat masalah yang sangat penting: Apakah hak kita juga telah terdigitalisasi?
Pada forum 2018, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) menekankan pentingnya tata kelola digital yang mementingkan inovasi dan teknologi berbasis data, berisiko melanggar data pribadi dan privasi. Pelajaran utama dari forum ini adalah bagaimana mencegah transformasi digital dari pelanggaran hak asasi manusia karena semakin banyak perusahaan dan pemerintah mendorong inovasi teknologi tanpa mengantisipasi dampaknya.
Kasus-kasus keamanan pribadi, kebocoran informasi, misinformasi, penipuan, serangan siber, dan aktivitas terlarang lainnya yang belum diatur, telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah tata kelola dapat menandingi percepatan pertumbuhan digital.
Indeks Ranking Digital Rights (RDR) tahun 2020 menguak masalah ini dalam evaluasi tata kelola digital 26 raksasa teknologi global, yang melayani lebih dari 4,6 miliar pengguna dengan pasar bernilai hampir US$11 triliun.
Perusahaan teknologi global dengan kinerja terbaik seperti Twitter, Ooredoo, dan Telefonica hanya mendapat nilai D (4—5 persen) dalam RDR 2020. Sementara itu, raksasa supply-chain Amazon berada di urutan terbawah dari 14 platform digital karena dilaporkan memiliki transparansi yang kurang dalam cara menangani atau mengamankan informasi pengguna dan kebijakan penyimpanan data. Temuan ini telah meningkatkan kewaspadaan bagi pemerintah mengenai apakah proses pembuatan kebijakan dapat menyeimbangkan ledakan ekonomi digital.
Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) tahun ini, hanya 128 dari 192 negara (66 persen) yang mengatur keamanan dan privasi data pribadi, sementara 10 persen sudah mulai menyusun peraturan dan 10 persen belum memiliki peraturan. Contoh terbaru adalah China, yang pemerintahnya memberlakukan peraturan ketat terhadap perusahaan digital dengan batasan yang jelas dan denda yang besar bagi pelakunya.
Bagaimana dengan Indonesia?
Pemerintah Indonesia telah menggaungkan Industri 4.0 dalam menanggapi tren global. Namun, kita masih menunggu pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi di DPR sebagai payung kebijakan. Tanpa undang-undang ini, para pemain digital tidak akan memiliki dasar hukum dan tidak dapat menerjemahkannya ke dalam kebijakan turunan masing-masing perusahaan.
Belajar dari kontroversi UU Cipta Kerja dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah seharusnya memberikan akses bagi masyarakat sipil untuk membahas RUU perlindungan data pribadi. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam merumuskan, memantau, dan mengevaluasi peraturan turunan.
Mengapa? Inti dari tata kelola digital adalah tata kelola antar entitas-individu, tentang bagaimana pemerintah mengatur perusahaan dan bagaimana perusahaan mengakomodasi hak individu. Dengan partisipasi masyarakat, pemerintah akan memiliki regulasi yang lebih sehat dan efektif untuk mengelola dunia digital.
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengumumkan secara terbuka fase persiapan untuk mengatur akuisisi data, perlindungan, keamanan dan skema insentif untuk memacu persaingan di antara para pemain kunci. Mengingat inisiatif ini, tiga rekomendasi berikut dapat membantu proses tersebut.
Pertama, pemerintah harus menyusun model bisnis end-to-end yang komprehensif yang menggunakan kerangka tata kelola yang tepat untuk menghindari “jebakan e-government” yang telah disosialisasikan melalui program nasional e-government (SBPE). Ruang lingkup tata kelola digital jauh lebih luas daripada e-government.
Seiring berjalan, huruf “e” disematkan untuk mewakili teknologi dalam istilah e-government, e-governance (tata kelola) dan e-democracy. Definisi operasional dari e-government dengan e-governance sering dicampuradukkan dengan meng-online-kan semua dokumen tanpa mengubah kerangka besar tata kelolanya.
Istilah teknologi digital telah mengubah definisi tata kelola menjadi menjadi lebih spesifik. Welchman (2015) mendefinisikan tata kelola digital sebagai “kerangka kerja untuk membangun akuntabilitas, peran, dan otoritas pengambilan keputusan untuk kehadiran digital organisasi”. Aspek utamanya terletak pada pengaturan kebijakan, strategi dan standar (berbasis aturan).
Ilya dan Syahraki (2020) menawarkan definisi alternatif tata kelola digital yang menekankan penggunaan prinsip (output-based) daripada tata kelola berbasis aturan (struktural). Pendekatan ini digunakan untuk menangani bisnis end-to-end di dunia digital. Memastikan prinsip tata kelola digital terarusutamakan dalam rancangan aliran informasi data di setiap proses bisnis akan memperkuat implementasi tata kelola digital secara keseluruhan, karena setiap sektor memiliki konteks yang unik.
Pendekatan terakhir menawarkan istilah teknis yang lebih jelas untuk tata kelola digital. Namun, ruang lingkupnya juga harus mencakup entitas pemerintah dan lembaga negara. Sebagai contoh, lihat PeduliLindungi, aplikasi pelacakan kontak COVID-19 yang diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan, JKN Seluler, aplikasi resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dan banyak aplikasi lainnya yang dikembangkan pemerintah. Apakah sebuah aplikasi melindungi privasi data atau tidak, itu bergantung pada pengetahuan teknis tim perancang dan vendor TI yang mendesain tampilan visual (interface) dan navigasi pengguna mereka.
Selanjutnya, berinvestasi dalam mendidik aparatur negara tentang pengetahuan digital. Kita bisa belajar dari Singapura dan Estonia, yang dari awal sudah mendidik para pembuat kebijakan dan pelaksana di pemerintahan. Berbekal ilmu tersebut, mereka dapat mengedukasi masyarakat melalui program-program pemerintah.
Kedua, Indonesia harus menstimulasi para pemain untuk mendukung kebijakan dengan cara mengadopsi indeks RDR global baik di tingkat nasional maupun lokal. Instrumen kebijakan tersebut akan mendorong tidak hanya perusahaan, tetapi juga instansi pemerintah untuk merefleksikan dan menyesuaikan model bisnis digital mereka berdasarkan kebutuhan masyarakat atau pelanggan.
Ini mirip dengan cara kerja sistem peringkat perusahaan digital. Kerangka yang sama dapat diterapkan pemerintah untuk mengubah pola pikir para pelaksana kebijakan, perusahaan, dan masyarakat, terutama dalam cara mengatur aplikasi mereka. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, instrumen kebijakan tersebut akan membentuk alur tata kelola digital di Indonesia.
Pada akhirnya, pemerintah perlu merangkul partisipasi publik dalam tata kelola digital Indonesia, karena inti dari kebijakan digital adalah tentang bagaimana teknologi mempengaruhi perilaku masyarakat dan sebaliknya. Setiap warga negara harus dapat mengambil bagian aktif dalam melindungi dan membentuk tata kelola digital. Dengan cara ini, interaksi dan sinergi antara pembuat kebijakan, pemain kunci, dan pengguna akan menjaga perkembangan teknologi yang seharusnya memberikan kesejahteraan sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang tampaknya sekarang dapat berubah hanya dengan sekali klik.
Ditulis oleh: Lenny Hidayat, SSos, MPP. Penulis adalah Spesialis Kebijakan Publik dan Tata Pemerintahan – The Partnership for Governance Reform (KEMITRAAN)
Artikel ini adalah opini penulis. Artikel ini pernah tayang di The Jakarta Post.