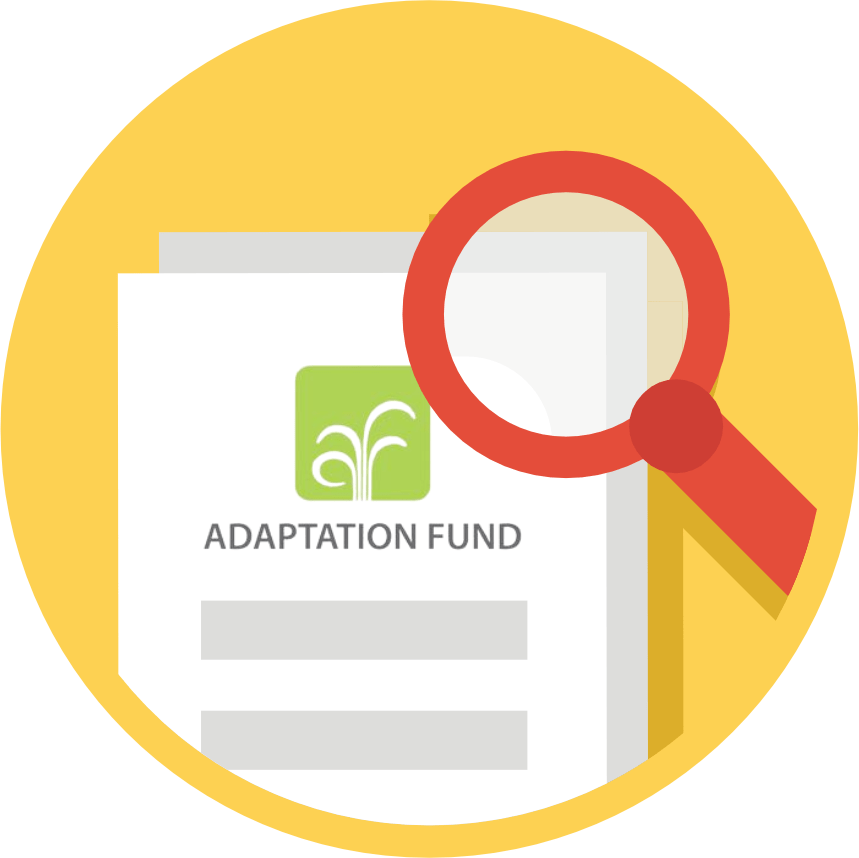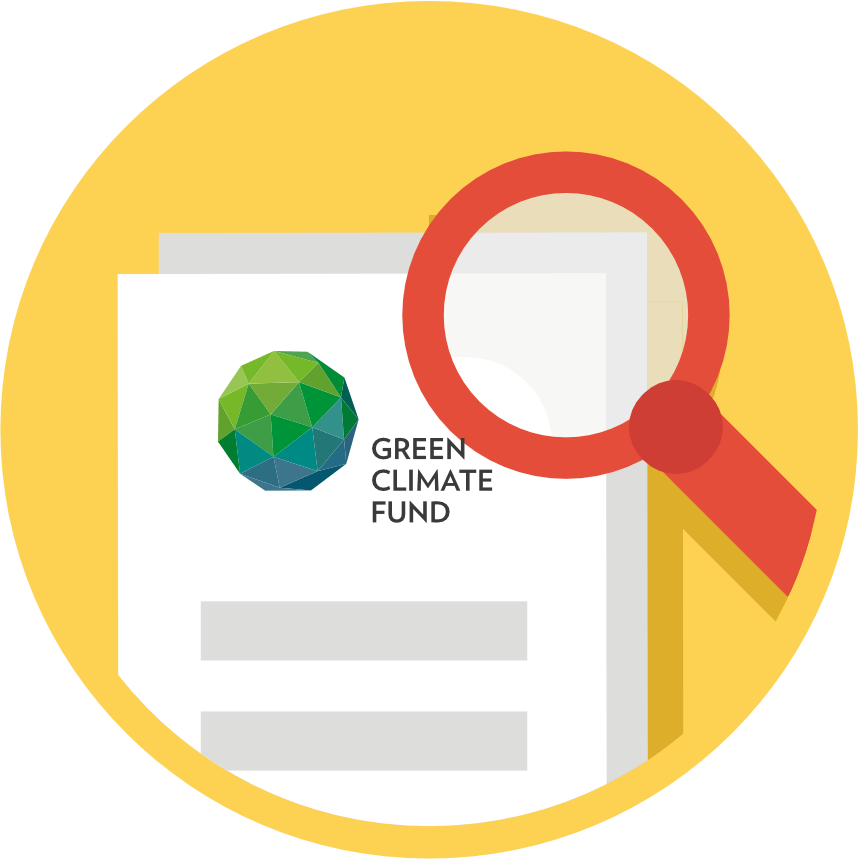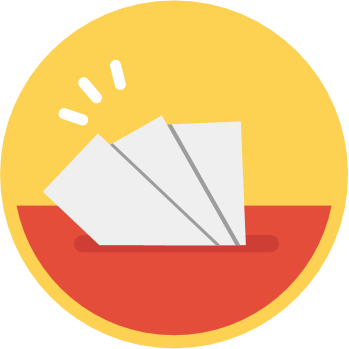Beberapa pekan lalu beredar video dari kanal Youtube tentang dua kelompok masyarakat bertengkar dan hampir terjadi perkelahian karena memperebutkan klaim pengelolaan hutan di Rembang, Jawa Tengah.
Kelompok pertama menganggap areal itu selama ini sudah mereka manfaatkan melalui kerjasama dengan Perum Perhutani. Sedang kelompok kedua mengklaim, areal itu sudah jadi kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) yang diserahkan pengelolaan kepada mereka oleh presiden pada 10 Maret 2023 di Blora, Jawa Tengah.
Presiden memang menyerahkan 19 surat keputusan persetujuan pengelolaan perhutanan social di KHDPK sekitar 21.000 hektar untuk kelompok masyarakat di tujuh kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Surat keputusan tidak hanya persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, tetapi sebagian keputusan areal indikatif perhutanan social pada KHDPK yang belum validasi.
Areal yang diperebutkan masyarakat tadi nampaknya termasuk dalam areal indikatif, yang karena tidak sosialisasi baik berujung konflik. Ke depan, kalau tidak diantisipasi maka kejadian saling klaim yang berujung konflik seperti dalam video itu bisa kembali terjadi.
Pengaturan KHDPK muncul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, merupakan turunan UU Cipta Kerja. Substansi pengaturan ini adalah pemerintah pusat mengambil alih kewenangan pengelolaan hutan di Jawa sekitar 1,1 juta hektar dari Perum Perhutani. Kawasan hutan itu antara lain untuk kepentingan rehabilitasi hutan, dan perhutanan sosial. Lebih detail pengaturan areal dan lokasi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.287/2022.
Terjadi pro kontra pasca regulasi ini terbit. Satu sisi, KHDPK dipandang sebagai koreksi atas kerusakan hutan Jawa yang dikelola Perhutani. Ia juga peluang bagi pemerintah pusat untuk penataan hutan lebih baik dengan keterlibatan para pihak.
Sisi lain, muncul persepsi KHDPK berpotensi lebih merusak kawasan hutan, terutama hutan lindung kalau dimanfaatkan masyarakat. Para penolak KHDPK bahkan sampai mengajukan gugatan pencabutan regulasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Pada 15 Februari 2023, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Permenlhk Nomor 04/2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK. Sebulan berikutnya, terbit beberapa surat keputusan persetujuan yang diserahkan presiden di Blora.
Waktu penerbitan persetujuan perhutanan sosial cepat di KHDPK patut diapresiasi, terlepas apakah karena ada momentum kunjungan kerja presiden atau tidak.
Kalau ditelisik lebih lanjut, terdapat perbedaan pengaturan perhutanan sosial dalam KHDPK dengan Permenlhk 09/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Secara umum, dalam Permenlhk 09/2021 persetujuan pengelolaan perhutanan sosial diberikan berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat (lembaga desa, kelompok tani atau gabungan kelompok tani, koperasi dan perorangan yang membentuk kelompok).
Penyusunan dokumen usulan dapat difasilitasi pendamping dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), penyuluh kehutanan, pendamping perhutanan sosial yang ditetapkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
Berdasarkan dokumen usulan yang masuk, KLHK memverifikasi administrasi dan verifikasi teknis atas subyek dan obyek usulan. Kalau semua sudah clear & clean, maka dirjen atas nama menteri menerbitkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial untuk 35 tahun.
Dalam Permenlhk 04/2023 terdapat perbedaan pengaturan dan prosedur tata laksananya. Pasal 3 peraturan ini disebutkan, menteri menetapkan dan mengelola KHDPK, sementara pada Pasal 4 menyebutkan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK oleh unit pelaksana teknis (UPT) perwakilan dari kementerian di daerah.
Tidak ada penjelasan khusus dari kata “dilaksanakan”, hingga secara tersurat disebutkan yang melaksanakan pengelolaan perhutanan sosial di KHDPK adalah UPT.
Proses pemberian persetujuan perhutanan sosial juga difasilitasi UPT. Prosesnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14-18 mulai bukan dari usulan kelompok masyarakat tetapi UPT rapat koordinasi mengundang para pihak di daerah untuk mengetahui informasi awal areal indikatif perhutanan sosial. Hasilnya, akan jadi rencana fasilitasi, termasuk mengetahui seberapa besar potensi konflik.
Kalau lokasi berpotensi konflik tinggi maka dirjen dapat mensupervisi atau bantuan teknis dalam pelaksanaan fasilitasi.
Selanjutnya, UPT akan menugaskan pendamping pemerintah pada KHDPK untuk fasilitasi. Proses ini dapat melibatkan organisasi pemerintah daerah (OPD) provinsi bidang kehutanan, UPT kementerian lain, cabang dinas kehutanan dan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial (Pokja PPS).
Dokumen usulan perhutanan sosial yang disusun dilaporkan dan diserahkan kepada UPT. Kemudian, UPT akan validasi usulan yang dapat dibantu para pihak yang memfasilitasi. Kalau dinilai layak maka dirjen atas nama menteri akan menerbitkan persetujuan perhutanan sosial di KHDPK.
Pendampingan dan peran kelompok masyarakat sipil
Perhutanan sosial dalam KHDPK tidak berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat tetapi hasil identifikasi dari UPT. Fasilitasi dan pendampingan juga oleh UPT yang menugaskan pendamping pemerintah pada KHDPK, demikian juga validasinya.
Dalam proses sampai mendapatkan persetujuan perhutanan sosial hampir tidak dimungkinkan peran organisasi masyarakat sipil. Padahal, selama ini cukup banyak organisasi masyarakat sipil mendampingi dan memfasilitasi komunitas untuk mendapatkan hak dan akses mengelola hutan melalui program perhutanan sosial. Juga cukup banyak kelompok masyarakat sipil yang mendukung KHDPK dan berada di barisan KLHK dalam kasus gugatan pencabutan kebijakan. Peran LSM disebutkan pada pasca mendapatkan persetujuan.
Setidaknya, ada tiga pasal yang menyebutkan peran LSM, yaitu dalam penyusunan rencana kelola perhutanan sosial (RKPS) yang dapat difasilitasi LSM (Pasal 40). Lalu, fasilitasi kegiatan pengembangan usaha (Pasal 42) dan dalam kerjasama pengembangan usaha (Pasal 76).
Mengenai pendampingan, Pasal 84 menyebutkan, pendamping perhutanan sosial pada KHDPK terdiri dari pendamping pemerintah, penyuluh kehutanan ASN dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat.
Pendamping pemerintah pada KHDPK adalah pendamping dari karyawan badan usaha milik negara bidang kehutanan yang ditugaskan dalam pendampingan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK.
Dengan kata lain pendamping ini adalah pegawai Perum Perhutani yang terdampak kebijakan KHDPK.
Mengacu pada Permenlhk No. P.76/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Swadaya Masyarakat disebutkan, penyuluh ASN atau dalam peraturan itu disebut penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak penuh oleh pejabat berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk penyuluhan kehutanan.
Sementara penyuluh kehutanan swadaya masyarakat adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lain dengan kesadaran sendiri mau dan mampu jadi penyuluh. Penyuluh ASN dan penyuluh swadaya masyarakat selain sebagai pendamping juga disebut sebagai pembina pendamping pemerintah pada KHDPK.
Dari situ muncul pertanyaan, apakah pengelolaan perhutanan sosial di KHDPK masih dapat disebut sebagai pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau berbasis negara?
Beberapa indikator yang menguatkan perhutanan sosial berbasis negara adalah pengelolaan program ini pada KHDPK dilaksanakan UPT, didampingi pendamping pemerintah pada KHDPK yang ditugaskan oleh UPT yang berasal dari karyawan Perum Perhutani. Pendanaannya, juga difasilitasi Perhutani.
Penyuluh ASN dan swadaya masyarakat meskipun dapat menjadi pendamping tetapi lebih ditempatkan sebagai pembina pendamping pemerintah KHDPK. Hampir tidak ada peran fasilitator dari LSM dalam proses ini.
Pelibatan penuh karyawan BUMN menjadi pendamping menjadi tantangan tersendiri. Selama ini, banyak kritik terhadap mereka di lapangan, seperti pungutan liar terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan. Dari sisi tata kelola, meskipun areal sudah diambil alih pemerintah pusat tetapi seperti belum berubah karena pengelola sebelumnya (Perhutani) masih memiliki peran signifikan dalam pengelolaan KHDPK.
Perlu perbaikan
Idealnya, penyusunan kebijakan dengan mempertimbangkan masukan para pihak, misal, melalui proses konsultasi publik sebelum peraturan ditetapkan. Kebijakan yang mengatur pengelolaan KHDPK tidak melalui proses ideal ini. Dampaknya, terkesan ada pihak yang ditinggalkan dalam proses, padahal pihak itu selama ini memiliki peran signifikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Jawa.
Sebaiknya, peraturan perhutanan sosial pada KHDPK dapat diperbaiki dengan lebih melibatkan para pendamping dan fasilitator dari kalangan LSM dan/atau perguruan tinggi atau organisasi masyarakat lain yang memiliki kemampuan memfasilitasi komunitas.
Selain itu, mereka seharusnya juga dilibatkan dalam proses koordinasi untuk identifikasi areal dan proses validasi. Selain karena pengalaman dan penguasaan lapangan, juga menjaga keterwakilan para pihak dalam proses.
Pelibatan pendamping pemerintah dari BUMN kehutanan mesti diseleksi, terutama latar belakang pengalaman kerja sebelumnya dalam berhubungan dengan masyarakat. Jangan sampai karena alasan sudah berkomitmen tidak akan pemutusan hubungan kerja lalu mempekerjakan kembali para karyawan yang selama ini berkinerja tidak baik. Ia akan berpotensi menimbulkan konflik dengan kelompok masyarakat.
Harapannya, pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK bisa lanjut dengan proses cepat, transparan dan memenuhi rasa keadilan. Tidak ada pihak yang ditinggalkan.
Subyek dan penerima manfaat utama semestinya komunitas yang selama ini hidup bergantung dari sumberdaya hutan, yang sebelumnya sudah memanfaatkan kawasan hutan, bukan orang-orang dari luar wilayah itu.
Perseorangan dengan latar belakang pendidikan kehutanan yang boleh jadi subyek pengelola perhutanan sosial di KHDPK semestinya berproses dengan komunitas setempat dengan posisi setara, tidak hanya jadikan komunitas sebagai sub-ordinat semata.
Harapan akhirnya, pemulihan hutan Jawa tak hanya dapat dilakukan pemerintah, tetapi bisa melibatkan masyarakat dan pihak lain dengan skema dan proses fasilitasi jelas. Juga, menafikan kepentingan-kepentingan elektoral dan upaya penguasaan lahan lebih luas dari para pihak yang tidak berhak.
Beberapa lokasi perhutanan sosial di Jawa, yang sudah berkembang baik, seperti di Kulon Progo dan Gunungkidul, Yogyakarta, dapat jadi model pembelajaran yang baik. Mereka berkembang melalui proses cukup panjang dan dinamis.
Penulis: Gladi Hardiyanto, Project Manager KEMITRAAN
Artikel ini telah tayang di mongabay.id