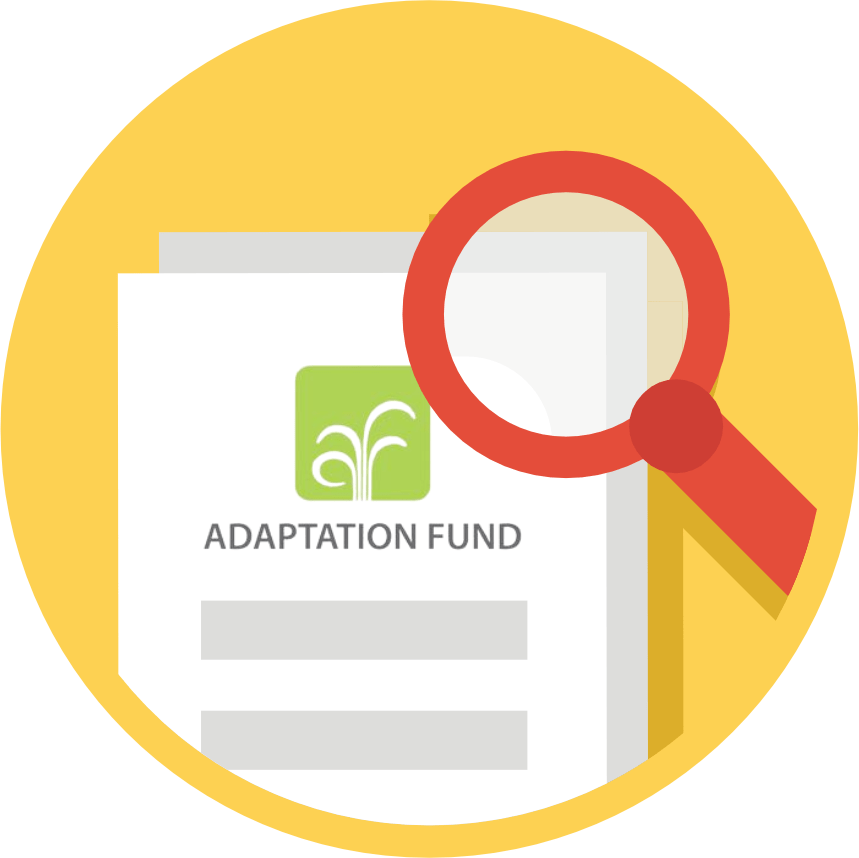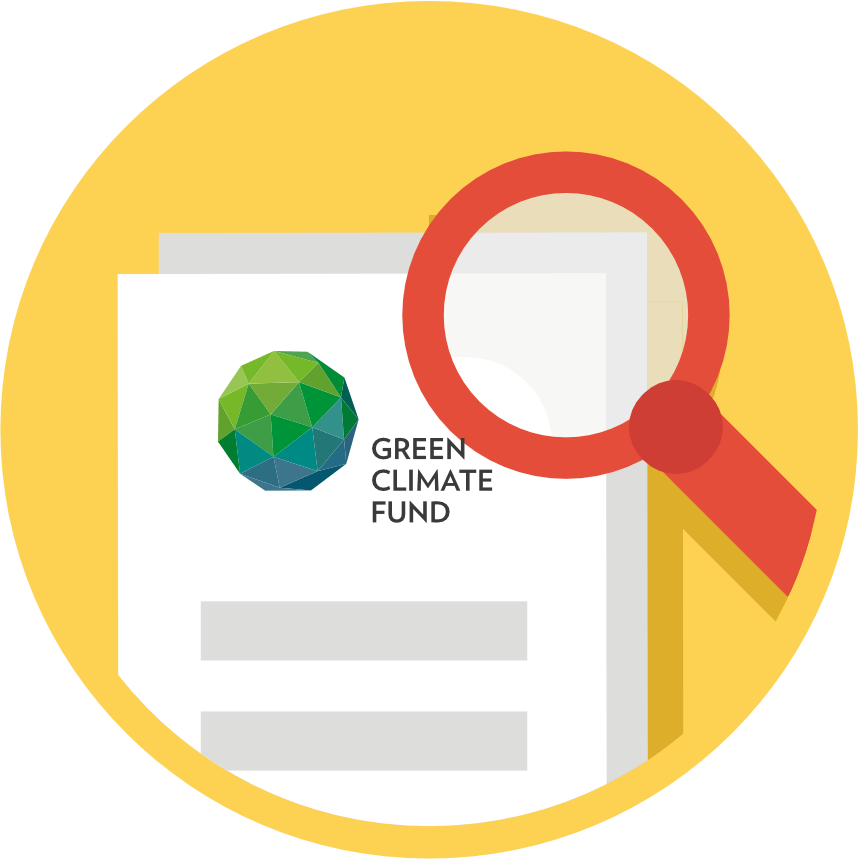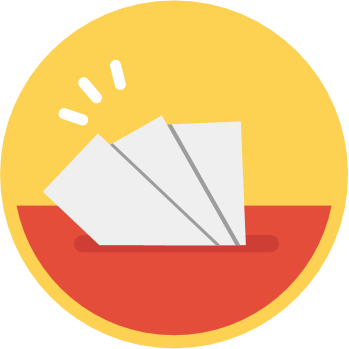Tepat setahun yang lalu yaitu April tahun 2022, Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun lahirnya UU ini merupakan hal baik yang dinantikan selama ini, tapi kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya dapat bergantung pada regulasi tersebut. Khususnya dalam konteks masyarakat adat yang selama ini sulit dalam mengakses layanan dasar, apalagi layanan hukum formal. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual merupakan setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki.

Sejak 2022, KEMITRAAN bersama dengan 10 mitra di 7 provinsi melakukan pendampingan terhadap masyarakat adat. Dalam pendampingan ini, kekerasan seksual banyak terjadi di komunitas adat dan umumnya berakhir dengan pelaku memberikan uang atau benda sebagai pengganti “kerugian” kepada korban, yang dinamakan praktek restitusi. Diskusi-diskusi mendalam yang dilakukan oleh KEMITRAAN dan sepuluh sub-mitra kemudian mengungkapkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di komunitas adat merupakan hasil dari praktik kekerasan berbasis gender yang sudah langgeng terjadi di masyarakat adat.
Merujuk kepada kondisi ini, di tahun 2023 KEMITRAAN kemudian menyusun Kertas Kerja Ruang Keadilan bagi Perempuan Adat dari Kekerasan Seksual. Dokumen kertas kerja ini turut melihat bagaimana UU TPKS dan RUU Masyarakat Adat, serta kaitannya dengan UU KUHP. Dokumen tersebut menganalisa bagaimana ketiga regulasi tersebut memberikan perlindungan bagi perempuan adat. Dokumen ini pun mendapatkan feedback dari kalangan organisasi masyarakat sipil, akademisi dan pembuat kebijakan berupa saran, yaitu pentingnya memiliki kajian atau hasil riset mengenai gambaran bentuk kekerasan seksual dari perspektif perempuan adat.
Kertas Kerja ini kemudian mendorong KEMITRAAN untuk melaksanakan Riset Etnografi bersama LAURA (Lembaga Antropologi) UGM yang dilakukan di 3 (tiga) lokasi yaitu Desa Wangga Meti di Sumba Timur, Desa Malancan di Kepulauan Mentawai, dan komunitas Etnis Cina Benteng di Tangerang. Hasil penelitian ini didiseminasikan pada tanggal 7 Maret 2024 bertepatan dengan momen peringatan hari perempuan sedunia. Sebanyak lebih dari 100 peserta hadir baik secara online dan offline dalam diseminasi hasil riset ini.
Acara ini dibuka oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam pernyataannya ia menyampaikan bahwa saat ini regulasi sudah ada namun belum ada yang secara spesifik mengatur tentang kekerasan seksual di masyarakat adat.
“Perlu menyelaraskan budaya, adat, tradisi, dengan hokum-hukum nasional. Harapannya hasil penelitian ini dapat kemudian nantinya ditarik menjadi rekomendasi kebijakan,” tambahnya.
Diseminasi ini menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Suhaeni selaku Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan KemenPPPA, Qurrota A’yun selaku Direktur KPAPO Bappenas, Muhammad Zamzam Fauzanafi selaku Kepala Peneliti LAURA UGM, dan Yasir Sani selaku Program Manager KEMITRAAN.
Narasumber yang hadir memaparkan pandangannya tentang bagaimana memberikan perlindungan bagi perempuan adat, khususnya juga bagi perempuan adat yang masih berstatus anak. Ayyun menyatakan bahwa banyak kasus yang tidak tercatat dan dilaporkan, sehingga perlu penyadaran kepada korban yang kerap tidak menyadari. Sehingga hal ini menjadi catatan penting bersama dan menjadi tantangan bersama untuk membangun kesadaran dan layanan sistem pelaporan terintegrasi. Hal ini sebagai bagian bagi instansi pemerintah untuk memberikan ruang perlindungan yang aman bagi korban kekerasan seksual di masyarakat adat.
Hal senada disampaikan Zamzam. Dalam rekomendasi riset ini, tim LAURA UGM merekomendasikan mengenai pentingnya konvergensi antara hukum adat dan hukum positif dalam menangani kekerasan seksual di masyarakat adat.
Sementara Yasir Sani sebagai Program Manager KEMITRAAN menyatakan bahwa hukum adat bersifat dinamis sehingga perlu memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Dengan demikian tidak tumpang tindih dengan hukum formal yang ada.
Riset ini juga turut melihat bagaimana perbedaan karakteristik ‘hukum adat’, kondisi geografi, dan status perempuan di masing-masing komunitas. Perbedaan karakteristik ini yang kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menemukan perbedaan cara pandang (ethnographic semantics) dan pengalaman (sense experience) masyarakat adat mengenai kekerasan seksual dan relasi sosial kultural yang melingkupinya.
Beberapa kesimpulan penting didapat dari hasil riset ini adalah masyarakat adat dengan struktur adat telah memiliki perbedaan pandangan atau sistem pengetahuan sendiri mengenai kekerasan seksual yang terejewantahkan dalam istilah-istilah atau bahasa lokal mereka yang secara detail menggambarkan berbagai tindakan yang dikategorisasikan sebagai kekerasan seksual. Kedua, salah satu penyebab kondisi di atas adalah perbedaan sistem sosial kultural yang kemudian berdampak pada terbentuknya hirarki sosial dan ketimpangan kekuasaan. Dan ketiga, dalam memberikan keadilan pada korban masih berpusat pada hukum perkawinan dan denda adat yang justru tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
Harapannya ketiga temuan penting ini nantinya akan dilanjutkan oleh KEMITRAAN untuk menjadi kertas posisi atau kertas rekomendasi bagi para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mendiseminasikan hasil temuan riset ini guna mempertajam rekomendasi KEMITRAAN dalam upaya menciptakan ruang aman bagi perempuan adat dari kekerasan seksual.