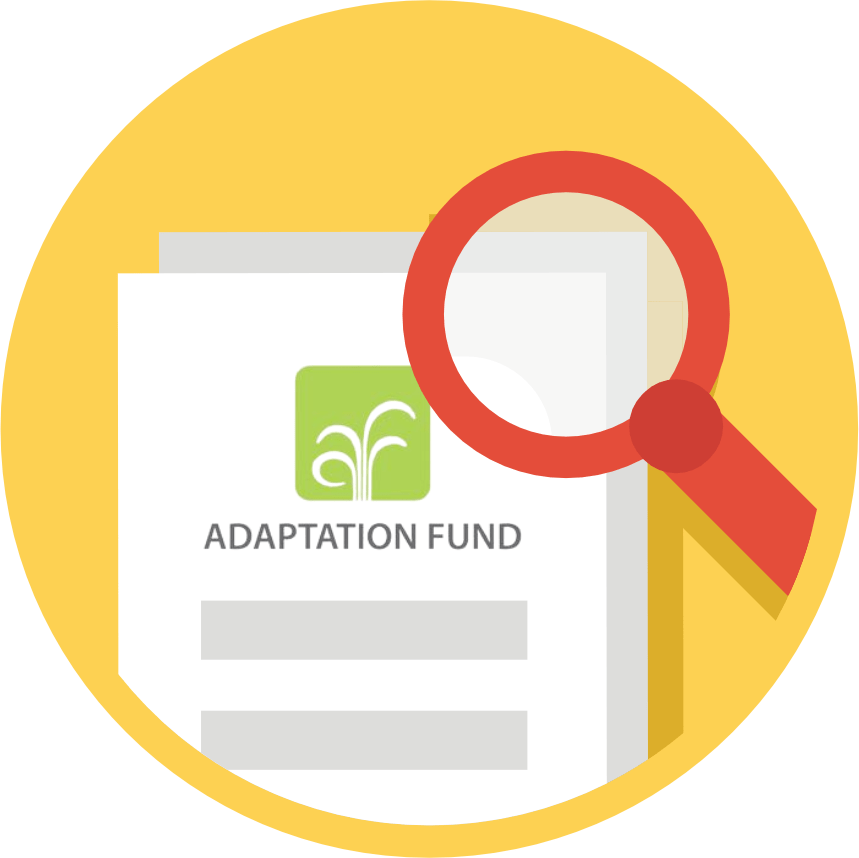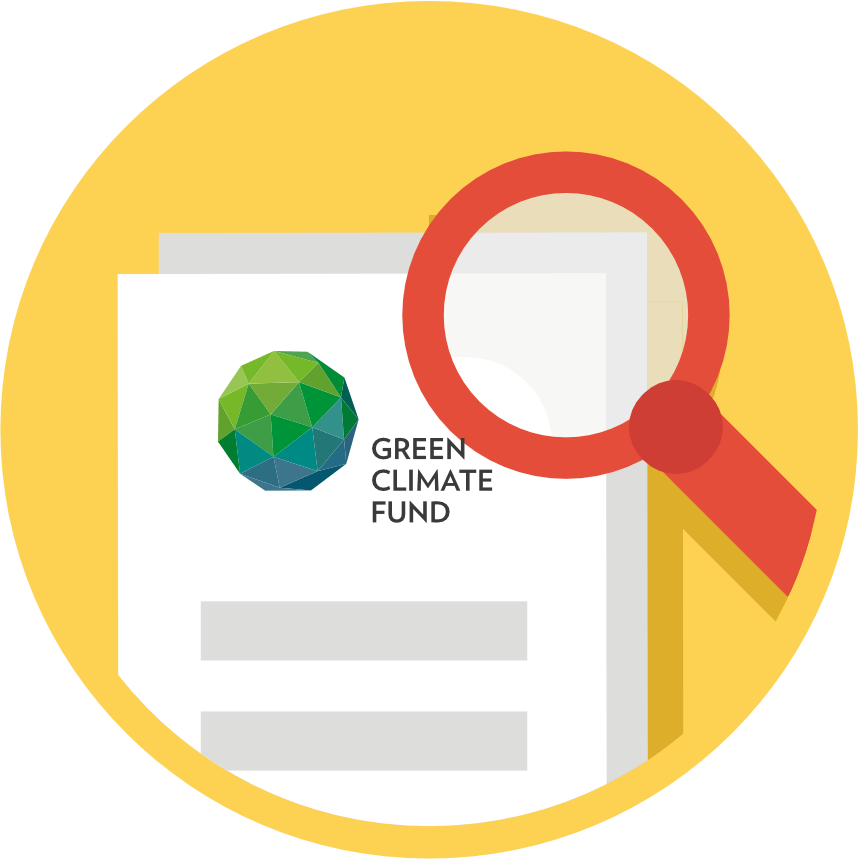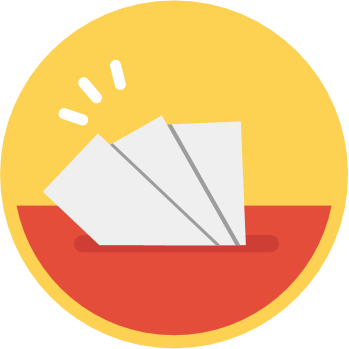Penulis : Hasantoha Adnan
Perhutanan Sosial bukanlah kebijakan yang lahir dari ruang kosong. Ia berangkat dari geliat masyarakat adat yang telah mengelola hutan, jauh sebelum Indonesia itu ada. Ia juga tumbuh dari para petani yang telah mengolah bentang alam dalam pranata titimangsa. Ia pun berinteraksi dalam kelindan pusaran kuasa negara dan swasta. Ia hadir jua dari suara-suara aktivis yang meyakinkan bahwa rakyat juga punya hak dalam kelola hutan. Ataupun akademisi yang meyakinkan bahwa hutan tak melulu tentang sains yang keras, tapi ada pengetahuan lokal yang juga turut andil dalam mengelola alam secara arif lagi lestari. Ia juga tumbuh dalam dinamika global, sejak ditahbiskan pada 1978 oleh FAO dengan “Forest for People.”
Kesemuanya itu menuju titik temu atas apa yang kemudian disebut sebagai perhutanan sosial. Sebuah kebijakan negara yang telah berevolusi dan memasuki era ketiga dalam perkembangannya.
Adalah Whina yang berupaya menangkap jaring-jaring makna itu. Perlahan dari seorang anak yang dibesarkan dalam dua tradisi besar: keluarga petani dan keluarga pedagang yang menak di pinggiran Bandung, lalu menempuh pendidikan konservasi di sebuah institute pertanian ternama hingga merangkak menjadi birokrat ulung yang jatuh iba pada nasib petani yang tinggal di gubuk tepi hutan, yang miskin dari hutan yang (pernah) kaya.
Dari rimbawan dengan gincu merah, blazer dan sepatu berhak yang kalau berjalan menimbulkan bunyi menjadi penanda profesionalitasnya di direktorat pengusahaan hutan. Lalu dipindah ke direktorat yang khusus mengurusi masyarakat di sekitar hutan. Perjumpaannya dengan Pak Sena, seorang akademisi yang membuka cakrawalanya dalam memahami relasi hutan dan masyarakat berpetualang di Krui dan Gunung Betung; atau pun Bilal, aktivis konservasi yang mengajaknya blusukan ke masyarakat adat penjaga hutan di Sumatera; Pun Myla, aktivis cum akademisi yang membawa perspektif gender dan semangat advokasi; maupun Pak Cipto birokrat tangguh yang memberinya kepercayaan untuk memperjuangkan kebijakan perhutanan sosial; hingga keluarga Bapak dan Ibu Pandur di kaki gunung Egon Flores yang memperlihatkan tanah sebagai penanda hidup; dan masih banyak sosok lain yang membentuknya menjadi seperti saat ini.
Buku yang dikemas dengan gaya data story telling ini boleh jadi genre baru dalam penyajian narasi sejarah gerakan sosial di Indonesia yang cenderung kering dan melupakan sisi subyektif manusia. Di buku ini, sosok-sosok dihadirkan untuk menampilkan bahwa kebijakan PS yang dikeluarkan kemudian adalah hasil pertemuan, dan tak jarang benturan kepentingan, dari para sosok baik secara langsung maupun tak langsung. Sosok menjadikan peristiwa-peristiwa yang dihadirkan dalam buku ini jadi lebih hidup.
Meski tampak sebagai fiksi, namun dengan catatan kaki dan hampir 200 buku referensi serta wawancara langsung dengan berbagai tokoh maupun catatan pribadi sang penulis, buku ini memastikan bahwa ini bukan cerita belaka. Penyebutan nama-nama “sekedar” menjaga anonimitas sosok sesungguhnya dalam panggung perhutanan sosial. Agar “tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu,” menjaga adab bahwa Perhutanan Sosial menjadi amal jariah bagi banyak sosok.
“Yellow Book” ditulis secara kolaboratif oleh duo ERNA: Erna Rosdiana birokrat yang lama malang melintang dalam isu perhutanan sosial dan baru saja pensiun, bersama Johanna Ernawati jurnalis kawakan, mampu menghadirkan kisah yang tak membosankan. Layaknya novel, kisah berdasarkan peristiwa nyata itu dikemaskan dengan alur turun naik yang mengasyikkan dan susah berhenti untuk membacanya, hingga sampai pada satu kesimpulan: betapa bermartabatnya petani hutan itu!
Bagi mereka yang terlibat dalam isu ini, buku ini bak nostalgia. Mengingatkan pada sosok-sosok yang beberapa diantaranya sudah membawa kisah ini sebagai jariahnya di alam sana (alfatihah untuk mereka). Bagi mereka yang baru saja terlibat dalam isu ini atau bagi kaum muda, buku ini menjadi bacaan yang wajib untuk tak melupakan sejarah dan merasa jadi “pahlawan kesiangan.”
Buku ini berakhir di tahun 2007 dengan keluarnya kebijakan Hkm yang memberikan izin pengelolaan hutan kepada kelompok masyarakat selama 35 tahun. Tahun yang masuk dalam era kedua (2000-2016), era transisi perkembangan perhutanan sosial. Tampaknya akan hadir buku kedua, dimana PS memasuki era ketiga (2016-sekarang) yang “naik kelas” menjadi kebijakan strategis nasional dan untuk pertama kalinya memiliki payung hukum dalam undang-undang Cipta Kerja, kendati dalam tekanan tak kalah penuh tantangan : digitalisasi dan oligarki berbasis lahan.