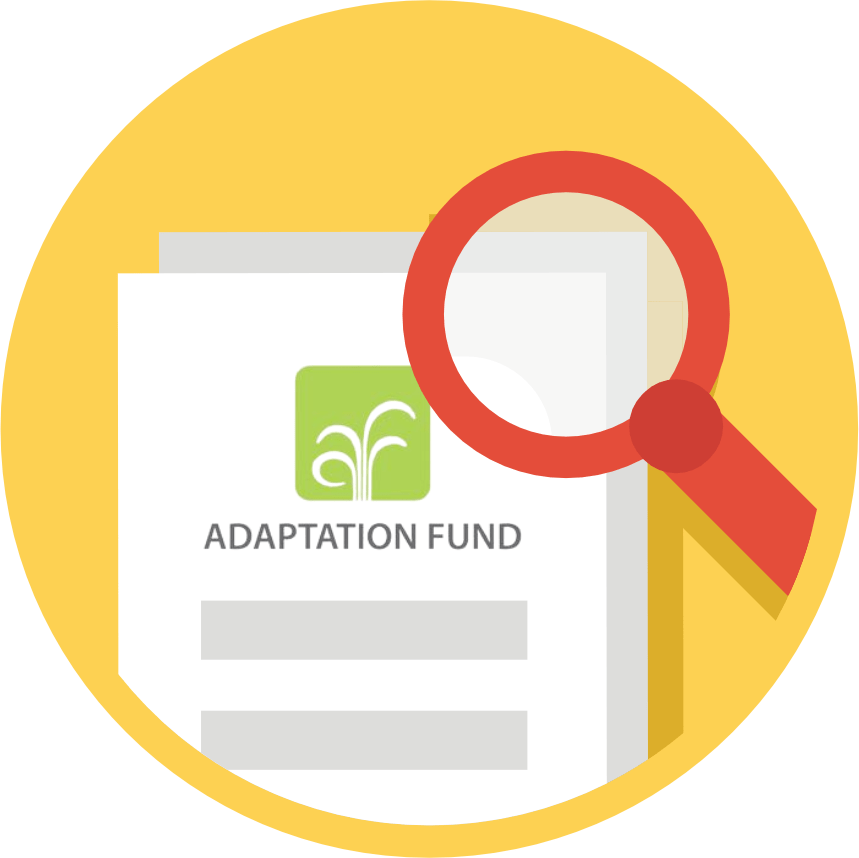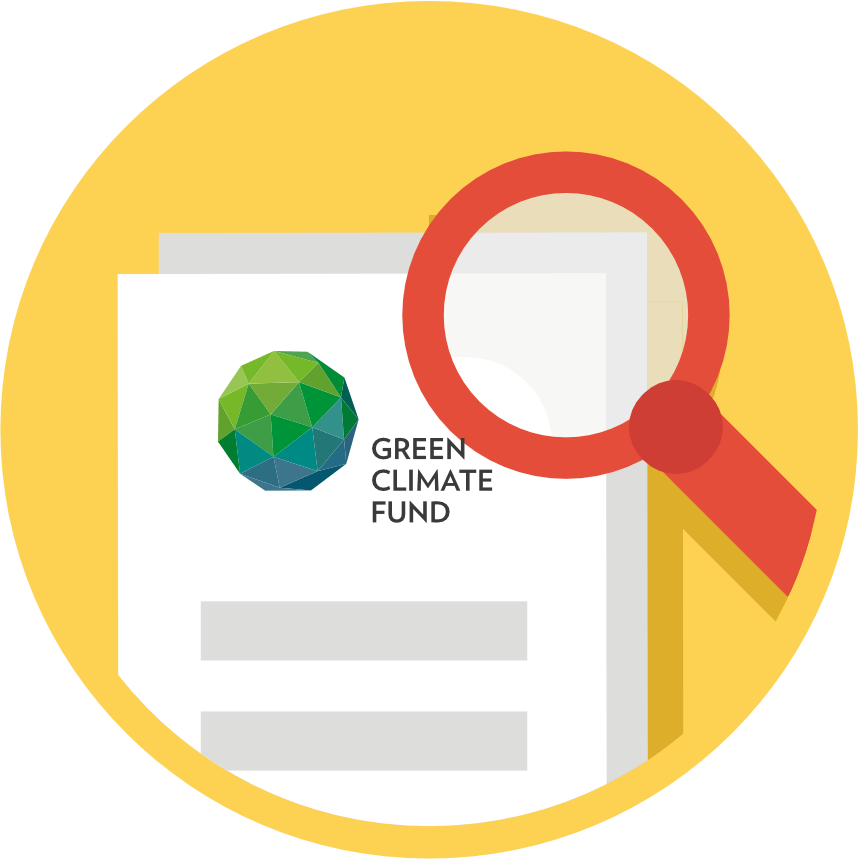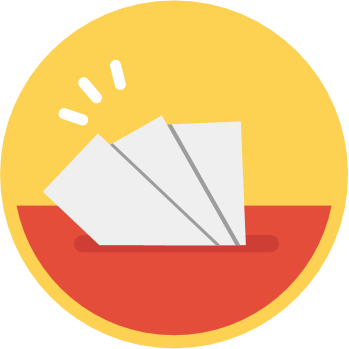Berdasarkan temuan dari Transparency International di Asia, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan dalam mengakses layanan publik. Seperti, lebih cenderung membayar suap untuk mendapatkan dokumen resmi. Perempuan yang tinggal di daerah pedesaan paling rentan untuk membayar suap untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Bahkan perempuan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan laki- laki untuk menyadari hak mereka untuk meminta informasi dari lembaga publik.
Hal-hal inilah yang membuat sextortion rentan dialami oleh perempuan. Bahkan menurut Global Corruption Barometer tahun 2020, Indonesia menempati negara dengan kasus sextortion terbanyak di Asia. (18%), diikuti dengan Sri Lanka (17%) dan Thailand (15%), dua kali lipat di atas rerata Asia (8%). Namun, perlu ada kerangka hukum yang lebih kuat untuk mengatur mengenai sextortion baik dari perspektif tindak pidana korupsi maupun kekerasan berbasis gender di Indonesia.
Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (22/2), berbagai perwakilan CSO hadir untuk menggali relasi gender, sextortion, dan tindak pidana korupsi. Judhi Kristantini, peneliti/konsultan USAID INTEGRITAS KEMITRAAN tentang sextortion, mengungkapkan bahwa ada dua hal yang membuat fenomena ini marak di Indonesia. “Pertama, adanya pemahaman korupsi yang masih terbatas pada uang semata. Padahal penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan itu sudah termasuk korupsi. Kedua pemahaman lingkup hubungan seksual yang belum sepenuhnya dipahami. Misal, tentang consent atau kesepakatan dalam berhubungan seksual,” jelas Judhi.
Upaya memotret bahwa sextortion adalah bagian dari penyalahgunaan kekuasaan juga penting dilakukan. “Gerakan anti korupsi harus bersatu dengan gerakan perempuan. Dua kejahatan ini banyak manifestasinya. Secara hipotesa, ketika kita menekan korupsi atau perilaku koruptifnya, mudah-mudahan angka kekerasan seksual juga menurun,” lanjut Judhi.
Alimatul Qibtiyah, Komisioner Komnas Perempuan, mengakui bahwa situasi sextortion umum dialami perempuan. Karena perempuan mengalami beban lebih berat tiga kali lipat, yaitu marjinalisasi, stigma dan subordinasi. “Situasi gender terhadap pelayanan publik masih timpang. Misal, informasi hanya diberikan kepada kepala keluarga yang laki-laki,” ujar Alimatul. Ia pun mengusulkan dalam hal sextortion, perlu dilakukan penyadartahuan dalam birokrasi pelayanan publik.
Sementara itu Andreas Nathaniel Marbun, peneliti Indonesia Judicial Research Society, memandang pentingnya memisahkan sextortion dan sex gratification. “Perbedaan mendasar antara keduanya adalah consent. Pelaku sex gratification, terlepas dari didasari oleh ketimpangan finansial, (menggunakan) mata uang seks (untuk mendapatkan keuntungan). Korban pemerasan seksual dalam sextortion tidak boleh ditangkap. Tapi pelaku suap seks dalam sex gratification harus dipidana.
Terkait definisi tersebut, Theodora, peneliti sextortion dari USAID INTEGRITAS yang hadir secara virtual menanggapi untuk berhati-hati dalam mendefinisikan sexual bribery. Seringkali terjadi penyuapan seksual terjadi antara dua pihak yang menyuap dan disuap. Tapi kemudian si penyuap menggunakan perempuan untuk dimanfaatkan sebagai bentuk suap seksual. “Relasi kuasanya harus dibuktikan dan dibuat menjadi jelas,” kata Theo.
Andreas juga mengusulkan untuk menguatkan narasi bahwa sextortion punya kerangka hukum yang kuat dan pelakunya bisa dijerat pidana. “Sextortion bisa dijerat UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) pasal 6C atau 12,” tandasnya.
KEMITRAAN sendiri melalui Proyek USAID INTEGRITAS saat ini sudah melakukan diseminasi hasil riset Keterkaitan Hubungan/Eksploitasi Seksual, Konflik Kepentingan dan Korupsi pada pemangku kepentingan, CSO, akademisi di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Kupang serta melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi. Ke depannya KEMITRAAN akan memasukkan isu hubungan seksual dan sextortion ini ke dalam usulan panduan konflik kepentingan bagi Lembaga negara/pemerintahan yang tengah disusun bersama ICW, TII dan Basel Institute on Governance.