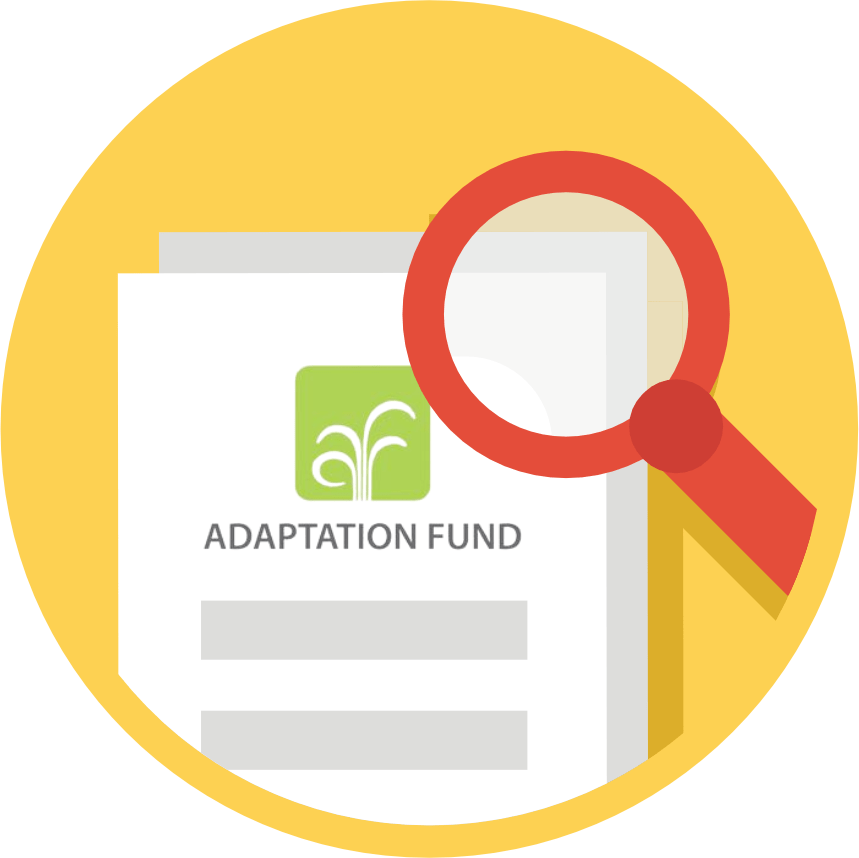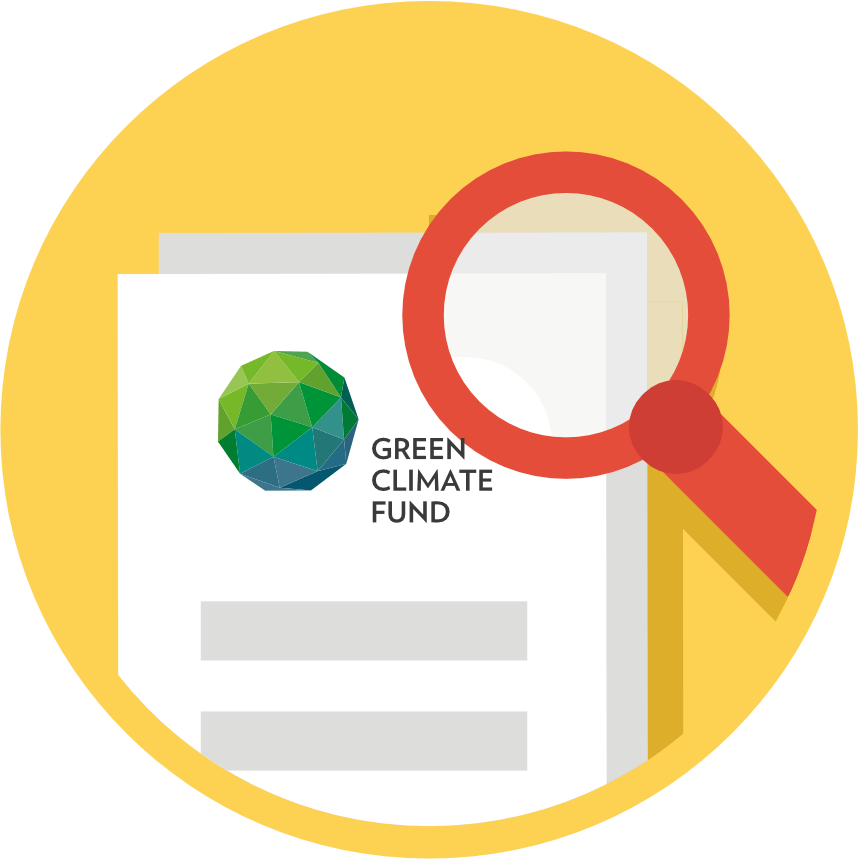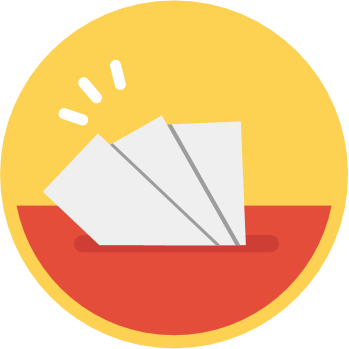Polemik transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 349 triliun yang dialamatkan ke Kementerian Keuangan (kemenkeu) masih terus bergulir. Ada ketidaksingkronan data antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU).
Dalam Rapat Kerja di Komisi XI DPR RI pada Senin (27/3), Menkeu terbaik Se-Asia Timur dan Pasific tahun 2020 ini mengklarifikasi sejumlah nilai transaksi yang disuplai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari angka Rp 349 triliun yang telah beredar luas di publik, yang benar-benar terkait dengan pegawai di Kemenkeu hanya berjumlah Rp 3,3 triliun. Sementara, Mahfud dan PPATK dalam rapat dengan Komisi III DPR RI menyatakan, jika transaksi keuangan mencurigakan terkait pegawai Kemenkeu terdiri dari dua kategori.
Kategori pertama berjumlah Rp 35 triliun yang melibatkan 461 entitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkeu. Sementara kategori kedua berjumlah Rp 53 triliun yang melibatkan ASN Kemenkeu dan pihak lain.
Akar masalah
Terlepas dari adanya masalah koordinasi antara Mahfud selaku Ketua Komite TPPU dan Sri Mulyani sebagai anggota, apa yang belakangan terjadi sebenarnya telah membuka mata kita bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang masih menemui jalan terjal.
Hal ini juga terkonfirmasi dari sejumlah laporan hasil analisis dan hasil pemerikaan PPATK yang dikirimkan ke penegak hukum, baru 30 persen yang ditindaklanjuti (Kompas, 29/09/21). Problem tersebut jika dicermati lebih jauh sebenarnya masih berkutat pada soal paradigma dan kapasitas aparat. Ikhwal paradigma aparat penegak hukum, masih seputar perlu atau tidaknya pembuktian tindak pidana asal TPPU yang sudah mengemuka semenjak rezim anti-pencucian uang pertama kali diterapkan di Indonesia tahun 2002. Hingga sekarang, paradigma tersebut masih sama: pembuktian tindak pidana pencucian uang harus diikuti dengan pembuktian tindak pidana asalnya (predicate crime). Mirisnya lagi, lembaga peradilan masih berpikiran serupa.
Teranyar, misalnya, dapat disimak pada kasus korupsi Simulator SIM. Majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) memerintahkan agar aset hasil sitaan penyidik hanya bisa digunakan untuk memenuhi pembayaran uang pengganti, sementara sisanya harus dikembalikan kepada terpidana. Padahal, selain didakwa korupsi, Djoko Susilo juga didakwa dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan semenjak tahun 2003. Jauh sebelum kasus korupsi simulator SIM terungkap pada 2012. Namun memang tidak bisa dipastikan tindak pidana asalnya merupakan korupsi atau bukan. Pada dasarnya, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (independent crime).
Anggapan harus ada pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu tentunya sangat keliru. Sama halnya dengan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP. Penadahan dilakukan atas benda atau barang hasil kejahatan yang tidak harus dibuktikan dulu siapa penanggungjawab atas kejahatan tersebut. Dalam proses persidangan, jaksa tidak harus membuktikan bahwa terdakwa mengetahui secara rinci kejahatan yang dilakukan terhadap barang menjadi objek penadahan. Misalnya, apakah barang itu hasil curian, penipuan atau penggelapan. Akan tetapi, terdakwa penadah patut diduga mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh secara tidak sah dengan cara tertentu.
Hal ini dapat dilakukan melalui bukti tidak langsung (circumstantial evidence). Hal ini akan lebih jelas jika kita memahami karakter tindak pidana pencucian uang. Pelaku mencuci uang tidak lain bertujuan menyembunyikan aktivitas ilegal yang ada di belakangnya. Maka, rezim anti-pencucian uang melalui pendekatan follow the money digunakan untuk membongkar kejahatan asalnya yang sudah berlalu. Sebagaimana yang diutarakan oleh Dirjen Perundang-undangan, Prof. Dr. Abdullah Gani pada rapat pembahasan RUU Pencucian Uang tahun 2002 di DPR, yang pada intinya mengatakan bahwa: “…Sebenarnya pencucian uang ini bisa merupakan pelengkap dari pemberantasan tindak pidana-tindak pidana yang pokok, misalnya korupsi. Kalau terjaring di sini mungkin akan bisa sampai lari mengusut tindak pidana korupsinya, atau kalau tindak pidana korupsinya tidak kena bisa tertangkap di sini. Kalau dikaitkan bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu korupsinya, diproses dahulu, maka pencucian uang ini tidak bisa diterapkan.” (Garnasih, 2003).
Financial crime Harus diingat bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan keuangan (financial crime). Maka sudah sepantasnya penyidik TPPU memiliki kapasitas penyidikan kejahatan keuangan (financial crime investigation). Selain menguasai teknik dasar penyidikan pada umumnya, penyidik TPPU harus pula mumpuni dalam hal forensik akuntansi dan forensik digital. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2021, semua penyidik tindak pidana asal dapat menyidik tindak pidana pencucian uang. Namun, belum semua lembaga yang ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kapasitas yang cukup sebagai financial investigator. Belum lagi masalah struktur kelembagaan serta ketidakjelasan jabatan fungsional penyidik yang masih menjadi penghambat para pemburu pelaku pencuci uang tersebut untuk bekerja maksimal. Berangkat dari problem ini, sudah selayaknya Mahfud selaku Ketua Komite TPPU segera menyudahi polemik yang terjadi. Sebagai seorang negarawan, Mahfud seyogyanya dapat mengajak seluruh anggota Komite TPPU untuk duduk bersama membicarakan langkah-langkah strategis dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketimbang terus berseteru pada masalah perbedaan data yang akan menyeret lebih jauh ke hal-hal yang kontra-produktif bagi masa depan rezim anti-pencucian uang di republik ini.
Penulis: Refki Saputra, Project Officer KEMITRAAN
Artikel ini telah tayang di kompas.com
Editor : Sandro Gatra