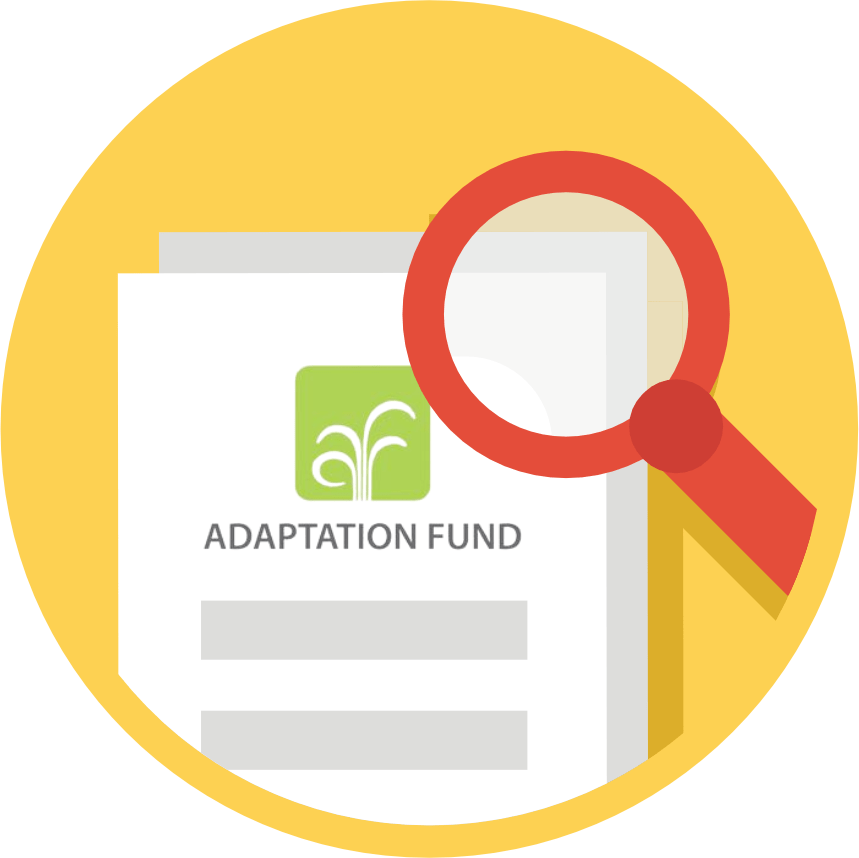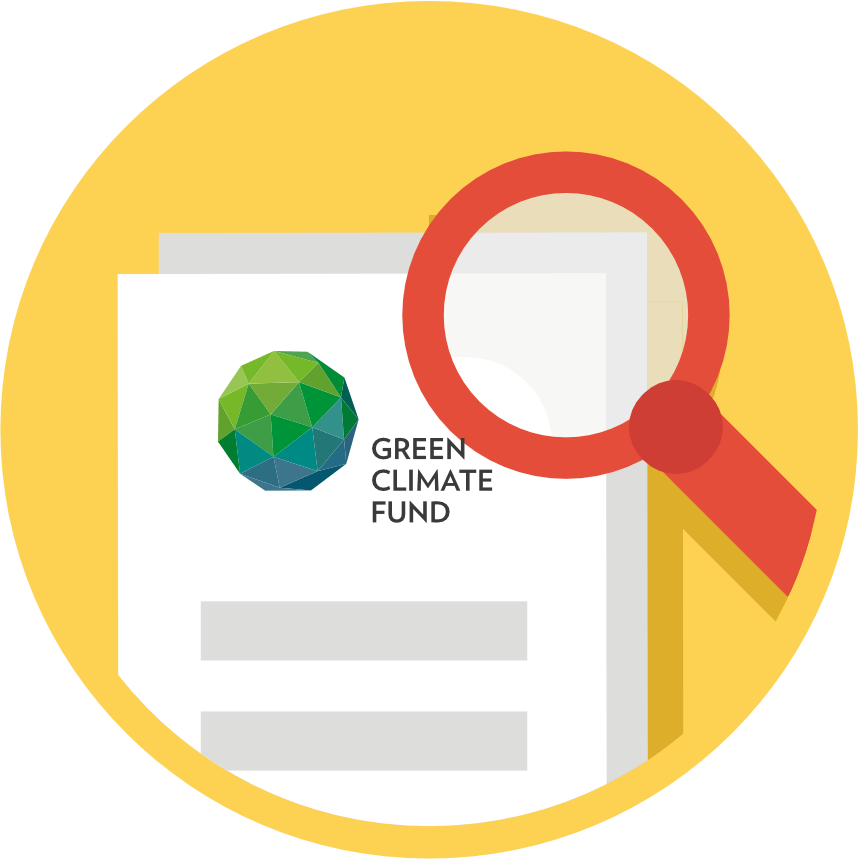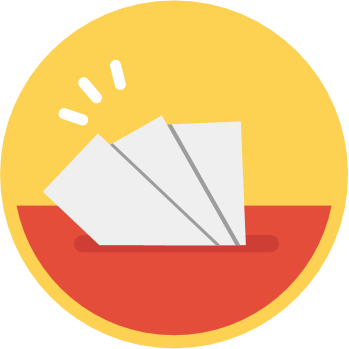Negara perlu segera mengubah cara pandang kepada para pembela HAM, karena kenyataannya sampai saat ini, mereka kerap dianggap sebagai ancaman, pengganggu pembangunan dan investasi di Indonesia.
“Padahal sejatinya, pembela HAM membantu negara untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya dilakukan oleh negara,” sebut peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputro kepada para peserta diskusi bertema Komitmen Negara dan Urgensi Pada Pelindungan HAM yang diselenggarakan oleh KEMITRAAN dan Kedutaan Besar Belanda di Ersmus Huis.

Lebih lanjut Ardi menyebut data Imparsial menunjukan bahwa selain masyarakat sipil dan masyarakat adat, jurnalis juga menjadi salah satu pihak yang memiliki risiko sangat tinggi saat meliput maupun melakukan investigasi di sektor lingkungan.
“Data ini menunjukan peran jurnalis dalam mengungkap kejahatan lingkungan sangat penting, sehingga mereka perlu dibungkam,” ungkapnya.
Kondisi ini seharusnya tidak terjadi, karena menurut Ardi keberadaan hukum menjadi benteng bagi para pembela HAM. “Oleh karena itulah ada pasal 66 di UU PPLH, ada pasal 15 UU KPK, dan ada pasal 18 di UU Pers untuk membentengi para pembela HAM dari para penyelenggara negara atau aparat pemerintah yang mudah tersinggung,” jelasnya.
Selain mengubah sudut pandang, Taufik Basari, anggota Komisi III DPR-RI menyebut kita juga perlu mengukur sejauh mana komitmen negara terhadap nilai-nilai HAM. Komitmen diukur dari empat hal; seberapa perhatian, seberapa penting isu HAM ditempatkan dalam kebijakan negara, seberapa membumi HAM dalam perbincangan masyarakat, dan seberapa paham penyelenggara negara dan masyarakat terhadap konsep HAM.
Sampai saat ini Taufik melihat persoalan HAM belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Isu prioritas saat ini menurutnya masih penanganan COVID dan pembangunan.
“Padahal kalau bicara prioritas yang saat ini, isu HAM jadi penting untuk memastikan penanganan COVID dan pembangunan berjalan tanpa melanggar HAM,” jelasnya. Kondisi ini menyebabkan isu HAM belum menjadi diskursus publik, sehingga masih jauh dari kepentingan di ranah politik dan komitmen dari parlemen. Untuk itu, Taufik menyarankan perlunya melakukan prakondisi.
“Saya mendukung revisi UU HAM. Tapi karena proses legislasi adalah proses politik, maka paling pertama dilakukan adalah mengangkat ini jadi diskursus, kepentingan bersama, kepentingan pembangunan dan kesejahteraan warga,” sarannya.
Sementara itu, Prof. Surya Jaya-Hakim Agung menyebut pelanggaran HAM terjadi karena tingkat pemahaman yang berbeda-beda. “Kalau penegak hukum sudah memiliki perspektif yang sama, maka ini (kriminalisasi) tidak akan terjadi,” jelasnya. Sementara pada tataran politik hukum dan komitmen negara, beliau menyebut tidak ada masalah. Karena hampir semua sektor mengatur perlindungan HAM. “Produk hukum yang dikeluarkan sudah cukup luar biasa banyaknya, oleh karenanya perlu disosialisasikan. Tidak hanya kepada masyarakat dan pejuang HAM, tapi juga penegak hukum,” pintanya.
Pada sisi penegakan hukum, Yudi Handono, Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Tindak Pidana Umum Lainnya di Kejaksaan Agung, menyebut pihaknya telah melakukan upaya pendekatan keadilan restorative justice, di luar pengadilan untuk meminimalisir adanya potensi kriminalisasi. “Kekuatan hukumnya sama dengan keputusan pengadilan,” jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga menyebut bahwa lembaganya memandang pembela HAM adalah warga yang berkontribusi sangat penting melakukan pendampingan, pengorganisasian, pengajaran dan peningkatan kapasitas masyarakat. Namun pada sisi lain sangat rentan mendapatkan serangan, oleh karenanya perlu perlindungan khusus. “Meski perlindungan HAM sudah diakui dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangan, namun sistem perlindungan HAM berbasis keamanan korban belum tersedia dengan memadai,” terangnya.

Dari perspektif korban pelanggaran HAM, negara menurut peneliti ICEL, Marsya Mutmainah, perlu mengimplementasikan konsep Anti- Strategic lawsuit against public participation (Anti-SLAPP) yakni aturan hukum yang melindungi hak dan akses masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya hak dan akses berpartisipasi, aturan ini juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tuntutan maupun gugatan hukum.
Lembaganya telah meneliti bagaimana mekanisme Anti-SLAPP yang efektif. Menurut Marsya ada dua kriteria. Pertama, mekanisme peninjauan dan pengguguran perkara sedini mungkin. “Begitu ada kriminalisasi seharusnya dihentikan dan tidak dilanjutkan, atau ada gugatan strategis biasanya nilainya sangat besar sehingga masyarakat yang berpartisipasi takut untuk melanjutkan partisipasinya.” Kedua, perlunya memberikan remedy (pembebanan biaya perkara, penggantian kerugian yang diderita akibat SLAPP, dan penggantian biaya kuasa hukum) yang harus ditanggung oleh pemohon SLAPP.
“Karena tidak jarang masyarakat yang berpartisipasi, kemudian di SLAPP, yakni upaya yang digunakan untuk menghentikan atau menghukum warga negara yang menggunakan hak politik mereka dengan tujuan mengalihkan perhatian publik dari isu publik menjadi ranah privat. Olehnya ada banyak kasus warga yang dijerat dengan SLAPP kehilangan pekerjaannya dan kehabisan dana karena terkuras untuk melawan gugatan yang besar ini,” terangnya.
Marsya berharap perlindungan HAM semakin diperkuat mengingat Indonesia adalah negara demokrasi, dan sudah saatnya Indonesia memiliki kebijakan anti-SLAPP agar masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan tanpa ada ketakutan dijerat hukum. “Harusnya masyarakat dirangkul dan menjadi kawan pemerintahan dalam membangun negeri ini. Kita sama-sama ingin maju, bukan pengganggu,” tutupnya.