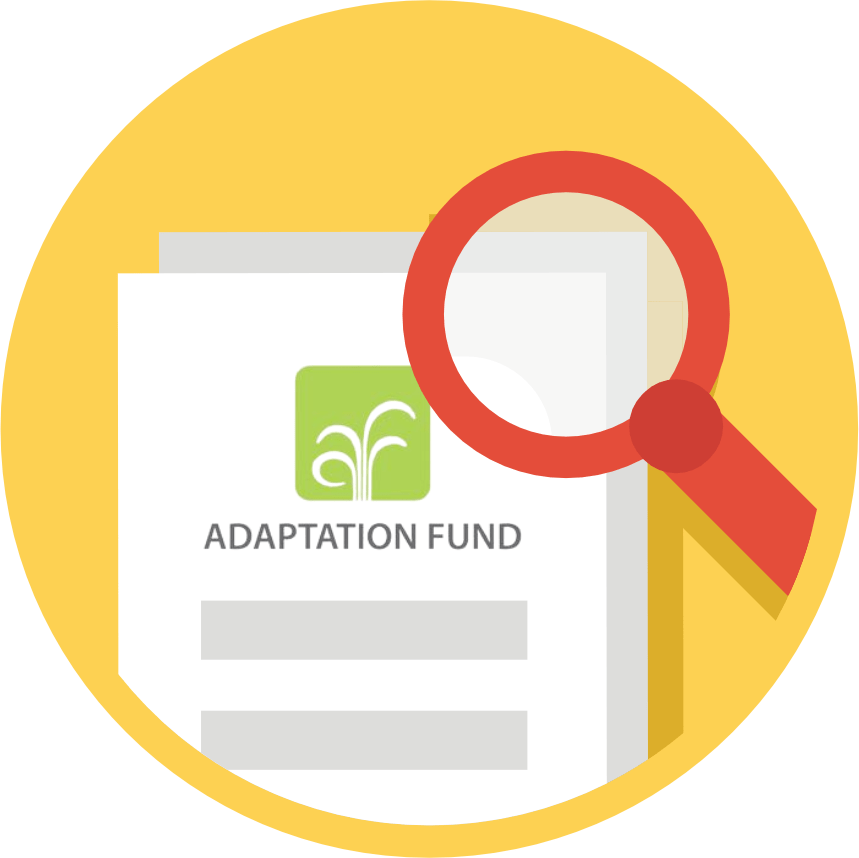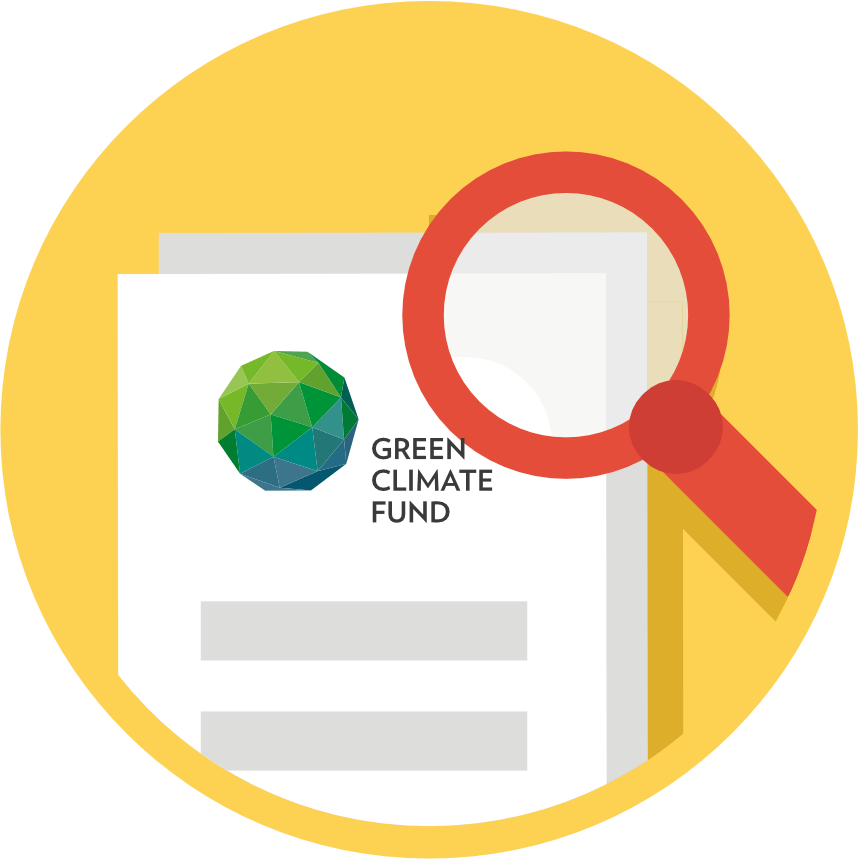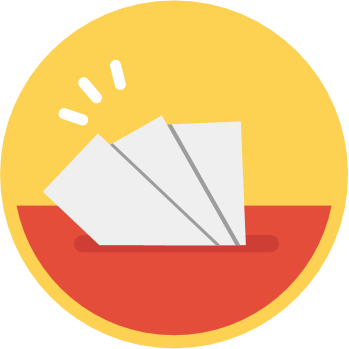Mataram (ANTARA) – Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang sering disebut inpres moratorium sawit akan segera berakhir di bulan September 2021 ini.
Sampai saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah akan melanjutkan atau menghentikan kebijakan tersebut. Banyak pihak, di antaranya koalisi organisasi masyarakat sipil, seperti Sawit Watch, Madani, Kaoem Telapak, Kemitraan, WALHI, Greenpeace Indonesia, Ecosoc Rights, dan lain-lain berharap dan mendesak agar kebijakan ini dapat dilanjutkan serta diperkuat tata kelola dan implementasinya.
Inpres moratorium sawit bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melestarikan lingkungan, termasuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) serta peningkatan pembinaan petani dan peningkatan produktivitas kebun sawit.
Di sisi lain tujuan tersebut dapat menggambarkan bahwa masih banyak permasalahan, baik Lingkungan, sosial dan ekonomi, pada pengelolaan kebun dan industri sawit. Dari sisi ekonomi, Tempo.Co (2021) menuliskan hasil wawancara Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menyebutkan kontribusi sawit masih cukup signifikan di masa pandemi COVID-19, di mana pada tahun 2020 jumlah produksi mencapai 51,58 juta ton dengan nilai ekspor mencapai 21,4 miliar AS. Dari angka tersebut estimasi kontribusi pajaknya mencapai Rp14-Rp 20 triliun per tahun.
Di sisi lain, besarnya kontribusi sawit terhadap perekonomian tersebut jika dihitung dengan banyaknya permasalahan di bidang ekologi dan sosial akan terlihat tidak signifikan. Kita semua mengetahui bahwa perkebunan sawit dibangun pada areal yang sebelumnya merupakan hutan, dengan melakukan pembukaan lahan (land clearing) yang seringkali dilakukan dengan cara membakar.
Berbagai kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Indonesia yang merugikan puluhan sampai ratusan triliun dan sebagian besar terjadi di luar kawasan hutan, termasuk di lokasi-lokasi perkebunan sawit.
Hal ini tidak saja berkontribusi pada kerusakan ekosistem hutan tetapi juga meningkatnya emisi GRK. Selain itu, pembangunan kebun sawit juga banyak berkonflik dengan masyarakat adat dan tempatan, baik konflik sejak awal karena proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa), yang tidak dilakukan oleh pemegang izin konsesi ataupun konflik-konflik yang terjadi setelah kebun sudah jadi, seperti pencemaran lingkungan, ketenagakerjaan dan lain-lain.
Selain itu, diketahui juga terdapat lebih dari 3,47 juta hektare (ha) kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan, yang ini tentu berkontribusi pada terjadinya deforestasi. Tidak hanya ditanam oleh masyarakat, tetapi lebih dari 800 ribu ha dari jumlah tersebut ditanam oleh konsesi, yang ini tentu saja secara de jure bisa dikatakan sebagai kebun sawit ilegal. Sayangnya, proses penegakan hukum terhadap kebun sawit yang ditanam ilegal ini tidak banyak dilakukan.
Evaluasi perizinan sebagai mandat dari inpres moratorium sawit tersebut hampir tidak dilakukan. Provinsi Papua Barat dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebetulnya tidak mendapat mandat dari Inpres moratorium sawit, yang melakukan proses evaluasi perizinan sawit. Evaluasi dilakukan kepada 24 perusahaan pemegang izin. Sebanyak 24 perusahaan tersebut memiliki total luas wilayah konsesi 576.090,84 ha.
Dari total luas wilayah tersebut, terdapat 383.431,05 ha wilayah yang bervegetasi hutan yang masih bisa diselamatkan dalam konteks penyelamatan sumber daya alam (SDA). Beberapa izin perusahaan sawit juga dicabut, terutama yang tidak prosedural dan/atau belum aktif melakukan kegiatan. Proses evaluasi perizinan, seperti di Papua Barat ini semestinya dapat dilakukan di berbagai provinsi lain, yang ini notabene adalah tujuan langsung dari instruksi presiden terkait dengan perbaikan tata kelola kebun sawit yang berkelanjutan.
Permanensi atau penguatan moratorium?
Belum ada dokumen formal hasil evaluasi dari tiga tahun pelaksanaan moratorium perizinan sawit yang disusun pemerintah dan dibuka untuk publik. Jika kita melihat kembali tujuan dikeluarkannya inpres moratorium sawit itu, maka masih jauh dari kata tercapai.
Terkait dengan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, selain proses evaluasi perizinan yang belum banyak dilakukan, hal lainnya misalnya adalah kepastian data luas perizinan dan tutupan lahan sawit yang berbeda, di mana luas perizinan mencapai lebih dari 14 juta ha tetapi tutupan lahannya lebih dari 16,3 juta ha.
Akibatnya dari sisi ekonomi saja terdapat potensi pajak penghasilan yang seharusnya diterima negara tetapi mengalir kepada pihak-pihak lain. Selain itu kepastian data luas kebun sawit rakyat serta data Hak Guna Usaha (HGU) yang terbilang masih tertutup untuk dapat diakses public. Transparansi dan partisipasi sebagai komponen tata kelola yang baik belum dapat diwujudkan.
Tujuan inpres untuk meningkatkan kapasitas petani dan produktivitas kebun sawit juga belum terwujud. Produktivitas kebun sawit rakyat rata-rata baru mencapai 3,16 ton tandan buah segar (TBS) per ha per tahun. Angka produktivitas kebun sawit rakyat di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan Malaysia, yang telah mencapai lebih dari 6 ton TBS per ha per tahun.
Jika saja kapasitas petani dan produktivitas kebun dapat ditingkatkan menjadi 6 ton TBS per ha saja maka terdapat potensi nilai ekonomi lebih dari Rp100 triliun yang dapat dihasilkan.
Dari gambaran ini dapat diketahui bahwa persoalan pengelolaan perkebunan bukan pada upaya untuk perluasan atau ekstenfikasi tetapi lebih pada intensifikasi kebun-kebun yang ada dengan revitalisasi pengelolaan, “replanting” kebun-kebun yang sudah tua serta penggunaan teknologi dan benih unggul. Sekali lagi, implementasi inpres moratorium sawit belum mampu meningkatkan produktivitas kebun sawit secara signifikan.
Dari paparan tersebut, sudah selayaknya pemerintah melanjutkan, dan bahkan memperkuat moratorium sawit.
Beberapa hal yang dapat dilakukan di antaranya membentuk dan memperkuat kelembagaan sekretariat pelaksana untuk membantu proses implementasi kegiatan; pengelolaan data base dan monitoring serta evaluasi atas apa yang sudah dilakukan kementerian/lembaga (K/L) lain dalam konteks implementasi rencana kerja dan poin-poin instruksi.
Selain itu, jangka waktu moratorium sebaiknya diperpanjang, tidak hanya 3 tahun tapi setidaknya 5 tahunan, agar lebih dapat diukur dan dinilai implementasinya. Penting juga untuk melibatkan K/L yang lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berpengalaman dalam melakukan supervisi evaluasi perizinan, BPDPKS yang mengelola dana sawit yang dapat dialokasikan selain untuk “replanting” juga untuk pengembangan kapasitas kelembagaan dan individu petani. Selain itu baik juga dilibatkan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Wacana lainnya, tidak hanya melakukan moratorium, akan tetapi justru lebih tegas lagi melakukan permanensi atas perizinan perkebunan sawit. Seperti penjelasan sebelumnya, kebun sawit di Indonesia sudah sangat luas, tetapi produktivitasnya masih rendah.
Jika dilakukan intensifikasi dan peningkatan produktivitas maka dengan luas kebun sawit di Indonesia akan dapat dihasilkan tambahan produksi dan devisa yang besar. Proses ini telah dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketika melakukan penghentian perizinan di lahan gambut dan hutan primer, setelah beberapa kali proses perpanjangan moratorium.
Akhirnya, dengan masih cukup karut marutnya pengelolaan sawit, jika pemerintah masih ingin lebih dipercaya rakyat maka tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan dan memperkuat moratorium sawit.
Ditulis oleh: Gladi Hardiyanto. Penulis bekerja di Partnership for Governance Reform (KEMITRAAN). Alumni Fakultas Kehutanan UGM dan Magister PS PSL IPB University.
Artikel ini adalah opini penulis. Artikel ini pernah tayang di Antaranews.com